Aroma
itu tercium lagi. Aroma tetesan air yang menyatu dengan tanah. Tetesan itu pun meluruhkan
debu-debu yang menebali dedaunan. Sungguh aroma yang menyejukkan. Aroma yang
selalu kurindukan. Ku hirup dalam-dalam molekul-molekul di udara untuk
meresapinya. Sejuk. Segar. Menerbangkan jiwa dan ragaku kembali dimasa-masa aku
masih mengenakan baju merah putih. Mengayuh sepeda miniku menerjang hujan.
Tanpa takut dan gelisah. Menantang langit yang menangis.
Tanpa
terasa mata ini terpejam. Dengan kedua lenganku mendekap erat tubuhku sendiri.
Semilir angin yang membawa butiran molekul H2O menerpa wajahku. Ku biarkan
tetesnya merengkuhku dalam kehangatan hujan. Semakin terasa nikmat. Ketika
terdengar gemuruh dari angkasa. Sungguh aku sangat merindukan saat-saat seperti
ini.
Bagaikan
bumi yang gersang berabad-abad dan mengiba kepada Tuhan agar memuaskan dahaga
ini dengan setetes air surga. Begitulah kira-kira yang ku rasakan ketika harus
bersabar beberapa bulan untuk menanti bulan Oktober tiba. Bulan pertama dimana
musim penghujan dimulai. Bulan pertama dimana tetes-tetes itu luruh dan
memuaskan kehausan bumi selama enam bulan lamanya.
Kala
jiwaku mulai melayang menikmati hujan yang hampir membawa tubuhku menari di
bawahnya, sepasang lengan mendekapku erat. Menahan tubuhku untuk tidak berlari
menari di bawah tetesan air langit. Deru napas yang hangat terasa mengalir
tepat di pundakku. Sebuah kecupan mais melayang tepat di keningku ketika mataku
terbuka dan menengok siapa gerangan yang menahanku menikmati hujan.
“Kenapa kamu menahanku?”
Sosok itu hanya tersenyum tanpa melepaskan dekapannya dari tubuhku.
“Aku ingin menari di bawah tetesan hujan. Aku ingin menikmati hujan pertama yang turun. Tidakkah kau tahu? Aku bagaikan gurun yang semakin gersang karena menanti hujan yang tak kunjung datang. Mengapa sekarang ketika ia datang kau menahanku?”
Sosok itu tetap tidak menjawab, hanya mendekapku lebih erat. Aku mulai memberontak berusaha melepaskan diri. Namun, semakin tubuh ini meronta, semakin erat pula tubuh itu mendekapku.
“Haruskah aku melepaskanmu? Haruskah aku membiarkan tubuhmu memucat diguyur hujan?”
“Aku hanya ingin menikmati hujan sebentar saja. Apa itu salah?”
“Kamu tidak berubah, masih saja keras kepala. Menikmati hujan itu tidak harus dengan menari di bawahnya.”
“Tapi...” Dekapan itu merenggang. Semakin renggang dan terlepas. Kini sosok itu berdiri tepat disebelahku. Menengadahkan tangannya menangkap butiran hujan. Matanya terpejam menghirup aroma tanah bercampur air yang segar.
“Aku sudah berpesan kepada hujan agar membuatmu sakit. Silakan pergi dan menari di bawahnya. Jika kamu memucat dan virus flu menyerangmu, jangan salahkan aku. Jangan panggil aku.” Sosok itu berlalu. Aku terdiam.
“Tunggu.” Sosok itu terhenti.
“Haruskah kamu melakukan itu?”
“Tentu. Wanita keras kepala di hadapanku ini harus segera mengerti bahwa itu bukanlah hal yang baik. Ingatlah sosok yang ada dalam rahimmu. Tegakah kamu menyengsarakannya? Tegakah kamu menyakitinya dengan menyakiti dirimu sendiri?”
Aku hanya diam dan membelai lembut perutku yang tidak lagi datar. Sebuah ruh sudah tertiup dan menghuni rahimku. Iya, hujan ini telah membuatku lupa akan tanggung jawabku saat ini. Maafkan Bunda, Nak. Aku menunduk dan terduduk di teras rumah menatapi butiran air yang masih menetes. Sosok itu mendekat dan duduk tepat disebelahku. Aku pun bersandar pada pundaknya.
“Hujan tidak harus dinikmati dengan menari dibawahnya. Tengadahkan tanganmu. Rasakan belaian hujan. Anggaplah itu sebagai salam selamat datang. Nikmati aromanya. Hujan akan terasa lebih indah.” Aku menengadahakn tanganku. Mataku terpejam. Aku merasa tangan-tangan hujan menjawab salamku. Ku hela napasku dan menikmati aroma tanah bercampur air yang kini juga sedikit becampur dengan aroma bunga kenanga atau mungkin melati. Entahlah. Dia memang benar. Menikmati hujan dengan cara seperti ini memang lebih indah.
“Kenapa kamu menahanku?”
Sosok itu hanya tersenyum tanpa melepaskan dekapannya dari tubuhku.
“Aku ingin menari di bawah tetesan hujan. Aku ingin menikmati hujan pertama yang turun. Tidakkah kau tahu? Aku bagaikan gurun yang semakin gersang karena menanti hujan yang tak kunjung datang. Mengapa sekarang ketika ia datang kau menahanku?”
Sosok itu tetap tidak menjawab, hanya mendekapku lebih erat. Aku mulai memberontak berusaha melepaskan diri. Namun, semakin tubuh ini meronta, semakin erat pula tubuh itu mendekapku.
“Haruskah aku melepaskanmu? Haruskah aku membiarkan tubuhmu memucat diguyur hujan?”
“Aku hanya ingin menikmati hujan sebentar saja. Apa itu salah?”
“Kamu tidak berubah, masih saja keras kepala. Menikmati hujan itu tidak harus dengan menari di bawahnya.”
“Tapi...” Dekapan itu merenggang. Semakin renggang dan terlepas. Kini sosok itu berdiri tepat disebelahku. Menengadahkan tangannya menangkap butiran hujan. Matanya terpejam menghirup aroma tanah bercampur air yang segar.
“Aku sudah berpesan kepada hujan agar membuatmu sakit. Silakan pergi dan menari di bawahnya. Jika kamu memucat dan virus flu menyerangmu, jangan salahkan aku. Jangan panggil aku.” Sosok itu berlalu. Aku terdiam.
“Tunggu.” Sosok itu terhenti.
“Haruskah kamu melakukan itu?”
“Tentu. Wanita keras kepala di hadapanku ini harus segera mengerti bahwa itu bukanlah hal yang baik. Ingatlah sosok yang ada dalam rahimmu. Tegakah kamu menyengsarakannya? Tegakah kamu menyakitinya dengan menyakiti dirimu sendiri?”
Aku hanya diam dan membelai lembut perutku yang tidak lagi datar. Sebuah ruh sudah tertiup dan menghuni rahimku. Iya, hujan ini telah membuatku lupa akan tanggung jawabku saat ini. Maafkan Bunda, Nak. Aku menunduk dan terduduk di teras rumah menatapi butiran air yang masih menetes. Sosok itu mendekat dan duduk tepat disebelahku. Aku pun bersandar pada pundaknya.
“Hujan tidak harus dinikmati dengan menari dibawahnya. Tengadahkan tanganmu. Rasakan belaian hujan. Anggaplah itu sebagai salam selamat datang. Nikmati aromanya. Hujan akan terasa lebih indah.” Aku menengadahakn tanganku. Mataku terpejam. Aku merasa tangan-tangan hujan menjawab salamku. Ku hela napasku dan menikmati aroma tanah bercampur air yang kini juga sedikit becampur dengan aroma bunga kenanga atau mungkin melati. Entahlah. Dia memang benar. Menikmati hujan dengan cara seperti ini memang lebih indah.





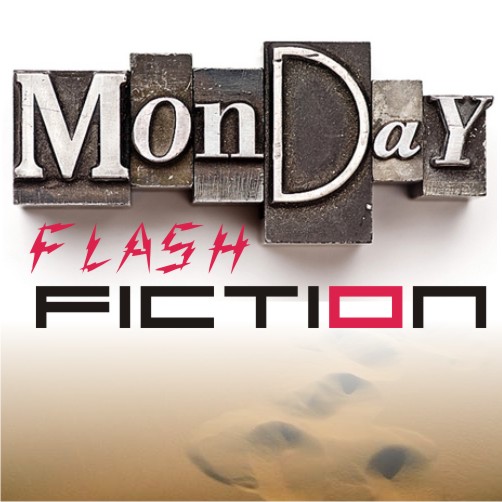
Tidak ada komentar :
Posting Komentar